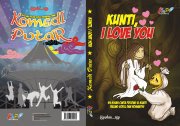Di bawah
gersang langit Probolinggo, 17 Juni 2017. 13.04. WIB.
Dear Langit,
Untuk langit kemarau yang
memisahkanku sebanyak 427,5 mil dengan kekasihku, apa kabarmu hari ini?
Kudengar, teriknya gemawan semakin menggelisahkan gersangnya rerantingan tersaput
angin gending mendebu di lautan pasir Gunung Bromo. Meriap, mendesing, hingga
sampai menjadi buliran hangat memanas di jemari kaki kekasihku—di aliran Sungai
Cimanis dalam kerlip musim tak berujung.
Duhai Langit yang menjadi saksi catatan sejarah pertemuanku dengan kekasihku di suatu kala 3 bulan 1 hari 12 jam 4 menit lalu di sebuah titik antara Probolinggo dan Cirebon, antara Jawa Timur
dan Jawa Barat, masihkah kau menjaga dirinya untukku? Dirinya yang kini hanya
sanggup kujangkau melalui sosial media. Jika kau menjaganya untukku, aku ingin
memberikanmu setangkup penjagaan alam,
agar kau tak lagi berderai dan tersedu kala sejenisku menistakan keberadaanmu.
Namun, andaipun tidak, aku tak apa. Tuhan telah sedemikian berbaik hati menjaga
dia untukku sejauh ini.
Kau ingat, Langit, pertemuanku
dengan Zein Elburqy di sebuah tempat antah berantah yang kulupa namanya?! Pun,
aku tak lagi bisa mengingat jejakan deskripsi alam di kitaranku. Hanya ada aku
dan dia dalam pusaran pesona tak bertuan. Ya, aku terpesona dan terkesima
padanya sejak pertemuan pertama kami. Sejak dia ada di situ dan berpakaian
serba biru yang mendadak menjadi warna favoritku. Waktu itu, dalam tegun tanpa
sadar, aku berucap, “You are really so amazing
in blue.” Bukan blue seperti yang
selalu menjadi kalimat klise dalam film romansa Hollywood mana pun juga, tetapi
navy blue, sebiru laut kedalaman hatiku
untuknya.
Selanjutnya,
dia menoleh padaku, tersenyum, dan menyebutkan nama. Senyum yang jika semesta
ini melihatnya, mereka takkan percaya. Kami bukan saja terjerat dalam arus
kekaguman tak bertuan antara Madura dan Sunda. Namun, juga elegi dewasa akhir
dan muda. Kala delapan tahun selisih kami tak menjadi penghalang hentakan dalam
dada.
Jika
kau ingin memandang sebelah mata atau mencibir pada kisah kami, tunggu dulu,
Langit! Tak pernahkah kukisahkan padamu tentang pengorbanannya yang tiada akhir
di kilometer 684 dari
tanah di pijakanku? Kala dia perkenalkan aku dengan satu persatu keluarganya
yang berjumlah empat derajat ke atas, samping, dan bawah. Belum lagi kerabatnya
yang berderet memanjang, sepanjang jalan Anyer-Panarukan. Sepanjang Cirebon-Probolinggo
Railways. Sepanjang itu pulalah dia
memupuk rasa sayangnya padaku. Pada lembaran tulisan yang kami rajut berdua
sepanjang kebersamaan kami dalam berbagai kuadran bahasa asing. Padahal,
hobinya bermain hadrah, bukan menulis. Hal yang disukainya adalah shalawatan,
bukan kosakata dan tata bahasa. Namun, semuanya melebur, serupa kopi bercampur
susu yang saling berpagut dalam tatakan cangkir aroma darahku dan denyar
nadinya.
Lalu,
tiba-tiba ketika dia mulai sanggup melantunkan deraian “Sengkok tresna ka ba’na—Aku cinta padamu” di suatu kala, aku
terkesiap. Mungkinkah arus damba dan puja tanpa jeda yang kurasa padanya,
terasa pula hingga dalam desir darahnya? Kala karuhun dan bebasan Sunda tampak
memikatku serupa macapat Madura yang dikisahkan oleh ayahku dulu. Kala aku
mulai berucap, “Abdi bogoh ka anjeun—Aku
cinta padamu” tak hanya di kata, tetapi dalam detak hela nadi jantungku.
Ah, Langit Kemarau di atas Pijakanku,
sampaikanlah pada kekasihku deru mengharu biru dalam gelenyar nadiku! Deru yang
takkan cukup dihela dalam uraian berbahasa Jerman, Jepang, dan Korea sebagai
penghubung cinta kami. Pun, Arab dan Inggris, yang tak pernah berhasil
menyampaikan setitik rasa kami. Sudikah kau, Langit, menjadi perantaraku
padanya dalam bahasa semesta?
Ku
bukan hanya ingin menjadi pelengkap bagi rusuknya yang hilang dulu. Namun, ku
ingin menjadi sumsum, yang akan ada kala raganya hilang seketika. Ku bukan saja
mendamba tawa dan derai cerianya. Namun, ku juga mendamba aliran kesedihan kala
dia mengadu padaku, alur keletihan kala dia bersandar di pundakku.
Dan,
astaga, kali ini kudapati, ku tengah merindukannya lagi setengah mati! Bukan.
Bukan senyum manisnya yang kurindukan. Namun, ekspresi wajahnya yang dibuat
seburuk mungkin untuk membuatku tersenyum kala ku mulai merajuk. Rambutnya yang
teracak semasai mungkin untuk membuatku memeluknya kala ku jatuh pada tingginya
tensi diri. Dan dia selalu ada di sana dengan tawa, senyum, segala yang dia
mampu berikan padaku.
Langit, andaikan suatu kala semua
itu hanya tinggal ilusi dan fatamorgana membayang, karena takdir tak
memperkenankan kami bersatu, aku tak apa. Sungguh! Aku sungguh cukup dengan
tingginya nilai kebersamaan kami. Pun, kerlingan kenangan sebanyak beberapa
rotasi bulan yang berganti di segala galaksi.
Aku
akan tetap percaya, dia selalu mencintaiku tanpa batas hingga ujung waktu.
Sepertimu, yang akan tetap menjadi naunganku hingga uraian waktu mengabu di
pijakanku. Aku akan tetap mencintanya tanpa batas hingga ke dunia tak
terdeteksi. Sepertinya, yang selalu menyayangiku selama ini menembus batas ruang-waktu
berdimensi.
Dan
kali ini, cukup saja kupanjatkan lagi doa di penghujung malam-malamku seperti
sedia kala pada pencipta kita berdua, Langit. Bukan doa nan mainstream semesta kepada Tuhannya, “Tuhan,
jika dia terbaik untukku, dekatkanlah! Namun, jika dia bukan terbaik dan hanya perantaraMu
dalam aku mengenalMu, ikhlaskan hati untuk melepasnya! Berikan padanya pilihan terbaik
menurut kehendakMu!” Namun, “Sungguh, aku berharap, akulah sebaik-baik kehendakMu
yang akan kucoba dekatkan lagi dalam detakan jarum yang terus berdetak. Karena
jika tidak, aku ingin menjaga kesucian janji cinta ini untukMu saja. Hingga
Kaupertemukan aku dengannya di naungan surgaMu. Aamiin.” Karena, aku hanya
ingin dia dan dia saja. Sejak dia ada di sana di dunia antah berantah yang
mempertemukan kami, sekejap di hadapan, hingga kembali terpautkan lintas maya
tak berkesudah.
Dalam saksi
berdarah kerinduan abu Bromo pada setangkup aromanya,
Riskaninda Maharani.